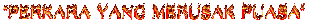“SIFAT PUASA NABI DI BULAN RAMADHAN”
Diringkas dari kitab : ” Sifat Saum Nabi fi Ramadhan “
(Penulis : Syaikh Salim bin Ied Al-Hilali & Syaikh Ali Hasan)



Ketahuilah wahai orang
yang diberi taufik untuk mentaati Rabbnya Jalla Sya’nuhu, yang
dinamakan orang puasa adalah orang yang mempuasakan seluruh anggota
badannya dari dosa, mempuasakan lisannya dari perkataan dusta, kotor dan
keji, mempuasakan lisannya dari perutnya dari makan dan minum dan
mempuasakan kemaluannya dari jima’. Jika bicara, dia berbicara dengan
perkataan yang tidak merusak puasanya, hingga jadilah perkataannya baik
dan amalannya shalih. Inilah puasa yang disyari’atkan Allah, bukan hanya
tidak makan dan minum semata serta tidak menunaikan syahwat. Puasa
adalah puasanya anggota badan dari dosa, puasanya perut dari makan dan
minum. Sebagaimana halnya makan dan minum merusak puasa, demikian pula
perbuatan dosa merusak pahalanya, merusak buah puasa hingga menjadikan
dia seperti orang yang tidak berpuasa.Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam
telah menganjurkan seorang muslim yang puasa untuk berhias dengan
akhlak yang mulia dan shalih, menjauhi perbuatan keji, hina dan kasar.
Perkara-perkara yang jelek ini walaupun seorang muslim diperintahkan
untuk menjauhinya setiap hari, namun larangannya lebih ditekankan lagi
ketika sedang menunaikan puasa yang wajib. Seorang muslim yang puasa
wajib menjauhi amalan yang merusak puasanya ini, hingga bermanfaatlah
puasanya dan tercapailah derajat Ketakwaan
Allah Ta’ala Menyebutkan dalam Firman-Nya :
“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas
kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar
kamu bertakwa” (Al-Baqarah : 183)
Karena puasa adalah pengantar kepada ketaqwaan, puasa menahan jiwa dari banyak melakukan perbuatan maksiat.
Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam, Bersabda :
“Puasa adalah perisai”
Inilah saudaraku se-Islam, amalan-amalan jelek
yang harus kau ketahui agar engkau menjauhinya dan tidak terjatuh ke
dalamnya, bagi Allah-lah untaian syair:
“Aku mengenal kejelakan bukan untuk
berbuat jelek tapi untuk menjauhinya, Barangsiapa yang tidak tahu
kebaikan dari kejelekkan akan terjatuh padanya”
YANG WAJIB DIJAUHI OLEH ORANG YANG SEDANG BERPUASA
Diantara hal yang wajib dijauhi oleh orang yang sedang berpuasa adalah :
Dari Abu Hurairah Radhiallahu ‘Anhu berkata, Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam bersabda :
“Barangsiapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta
dan (tetap) mengamalkannya, maka tidaklah Allah Azza wa Jalla butuh
(atas perbuatannya meskipun) meninggalkan makan dan minumnya”
( HR. Bukhari)
Dari Abu Hurairah Radhiallahu ‘Anhu berkata, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam bersabda :
“Puasa bukanlah dari makan, minum (semata), tetapi puasa itu menahan
diri dari perbuatan sia-sia dan keji. Jika ada orang yang mencelamu,
katakanlah: Aku sedang puasa, aku sedang puasa” (HR. Ibnu Khuzaimah dan
Al-Hakim)
Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam mengancam
dengan ancaman yang keras terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan
tercela ini.
Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam bersabda :
“Berapa banyak orang yang puasa, bagian (yang dipetik) dari puasanya
hanyalah lapar dan haus (semata)” (HR. Ibnu Majah, Darimi, dan Ahmad)
Sebab terjadinya yang demikian adalah karena orang-orang yang
melakukan hal tersebut tidak memahami hakekat puasa yang Allah
perintahkan atasnya, sehingga Allah memberikan ketetapan atas perbuatan
tersebut dengan tidak memberikan pahala kepadanya. Oleh sebab itu Ahlul
Ilmi dari generasi pendahulu kita yang shaleh membedakan antara
larangan dengan makna khusus dengan ibadah hingga membatalkannya dan
membedakan antara larangan yang tidak khusus dengan ibadah hingga tidak
membatalkannya.
Banyak perbuatan yang harus dijauhi oleh orang yang puasa, karena
kalau perbuatan ini dilakukan pada siang hari bulan Ramadhan akan
merusak puasanya dan akan berlipat dosanya. Perkara-perkara tersebut
adalah.
Allah Azza Sya’nuhu berfirman :
“Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang
hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang)
malam” (Al-Baqarah : 187)
Difahami bahwa puasa itu (mencegah) dari makan dan minum, jika makan
dan minum berarti telah berbuka, kemudian dikhususkan kalau sengaja,
karena jika orang yang puasa melakukannya karena lupa, salah atau
dipaksa, maka tidak membatalkan puasanya. Masalah ini berdasarkan
dalil-dalil.
Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam, bersabda :
“Jika lupa hingga makan dan minum, hendaklah menyempurnakan puasanya,
karena sesungguhnya Allah yang memberinya makan dan minum” (HR. Bukhari
dab Muslim)
Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam, bersabda :
“Allah meletakkan (tidak menghukum) umatku karena salah atau lupa dan
karena dipaksa” (HR. Thahawi, Al-Hakim, Ibnu Hazm, dan Ad-Darukutni)
Karena barangsiapa yang muntah karena terpaksa maka tidak membatalkan puasanya.
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :
“Barangsiapa yang terpaksa muntah, maka tidak wajib baginya untuk
mengqadha’ puasanya, dan barangsiapa muntah dengan sengaja, maka wajib
baginya mengqadha’ puasanya” (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)
Jika seorang wanita haidh atau nifas, pada satu bagian siang, baik di
awal ataupun di akhirnya, maka mereka harus berbuka dan mengqadha’
kalau puasa tidak mencukupinya.
Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam, bersabda :
“Bukankah jika haid dia tidak shalat dan puasa ? Kami katakan : “Ya”,
Beliau berkata : … Itulah (bukti) kurang agamanya” (HR. Muslim)
Dalam Riwayat Yang Lain, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam, bersabda :
“Berdiam beberapa malam dan berbuka di bulan Ramadhan, ini adalah (bukti) kurang agamanya”
Dalam Riwayat Mu’adzah, Disebutkan :
“Aku pernah bertanya kepada Aisyah : ‘ Mengapa orang haid mengqadha’
puasa tetapi tidak mengqadha shalat?’ Aisyah berkata : ‘Apakah engkau
wanita Haruri, Aku menjawab : ‘Aku bukan Haruri, tapi hanya (sekedar)
bertanya’. Aisyah berkata : ‘Kamipun haidh ketika puasa, tetapi kami
hanya diperintahkan untuk mengqadha puasa, tidak diperintahkan untuk
mengqadha’ shalat” (HR. Bukhari dan Muslim)
Yaitu menyalurkan zat makanan ke perut dengan maksud memberi makan
bagi orang sakit. Suntikan seperti ini membatalkan puasa, karena
memasukkan makanan kepada orang yang puasa. Adapun jika suntikan
tersebut tidak sampai kepada perut tetapi hanya ke darah, maka itupun
juga membatalkan puasa, karena cairan tersebut kedudukannya menggantikan
kedudukan makanan dan minuman. Kebanyakan orang yang pingsan dalam
jangka waktu yang lama diberikan makanan dengan cara seperti ini,
seperti jauluz dan salayin, demikian pula yang dipakai oleh sebagian
orang yang sakit asma, inipun membatalalkan puasa.
Imam Syaukani, berkata:
“Jima’ dengan sengaja, tidak ada ikhtilaf (perbedaan pendapat)
padanya bahwa hal tersebut membatalkan puasa, adapaun jika jima’
tersebut terjadi karena lupa, maka sebagian ahli ilmu menganggapnya sama
dengan orang yang makan dan minum dengan tidak sengaja.” (Dararul
Mudhiyah)
Ibnul Qayyim, berkata :
“Al-Qur’an menunjukkan bahwa jima’ membatalkan puasa seperti halnya
makan dan minum, tidak ada perbedaan pendapat akan hal ini” (Kitab
Zaadul Ma’ad)
Dalilnya Adalah Firman Allah Ta’ala :
“Sekarang pergaulilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian” (Al-Baqarah : 187)
Diizinkannya bergaul (dengan istri) di malam hari, (maka bisa)
difahami dari sini bahwa puasa itu dari makan, minum dan jima’.
Barangsiapa yang merusak puasanya dengan jima’ harus mengqadha’ dan
membayar kafarat,
Abu Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu, berkata :
“Pernah datang seseorang kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa
sallam kemudian ia berkata, ‘Ya Rasulullah binasalah aku!’ Rasulullah
bertanya, ‘Apa yang membuatmu binasa?’ Orang itu menjawab, ‘Aku menjimai
istriku di bulan Ramadhan’. Rasulullah bersabda, ‘Apakah kamu mampu
memerdekakan seorang budak?’ Orang itu menjawb, ‘Tidak’.
Rasulullah bersabda, ‘Apakah engkau mampu memberi makan enam puluh
orang miskin?’ Orang itu menjawab, ‘Tidak’ Rasulullah bersabda,
‘Duduklah’. Diapun duduk. Kemudian ada yang mengirim satu wadah korma
kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam .
Rasulullah bersabda, ‘Bersedekahlah’, Orang itu berkata, ‘Tidak ada
di antara dua kampung ini keluarga yang lebih miskin dari kami’.
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam pun tertawa hingga terlihat
gigi serinya, lalu beliau bersabda, ‘Ambillah, berilah makan keluargamu”
(HR. BUkhari, Muslim, Baghawi, Abu Dawud, Ad-Darimi, Ibnu Majah, Ibnu
Abi Syaibah, Ibnu Khuzaimah, Ibnul Jarud, Syafi’i dan Abdur Razak)
Ketahuilah wahai sauadaraku se-Islam
mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman agama kepada kita, bahwasanya
mengqdha’ puasa Ramadhan tidak wajib dilakukan segera, kewajibannya
dengan jangka waktu yang luas berdasarkan satu riwayat
Adapun Dalilnya adalah :
Dari Sayyidah Aisyah Radhiyallahu ‘anha, berkata :
“Aku punya hutang puasa Ramadhan dan tiak bisa mengqadha’nya kecuali di bulan Sya’ban” (HR. BUkhari dan Muslim)
Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani :
“Dalam hadits ini sebagai dalil atas bolehnya mengakhirkan qadha’ Ramadhan secara mutlak, baik karena udzur ataupun tidak.”
Sudah diketahui dengan jelas bahwa bersegera dalam mengqadha’ lebih
baik daripada mengakhirkannya, karena masuk dalam keumuman dalil yang
menunjukkan untuk bersegera dalam berbuat baik dan tidak menunda-nunda,
hal ini didasarkan ayat dalam Al-Qur’an.
“Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian” (Ali Imran : 133)
Dalam Ayat Yang Lain Disebutkan :
“Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya” (Al-Mu’minuun : 61)
Hal Ini Berdasarkan firman Allah Ta’ala :
“Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain” (QS.
Al-Baqarah : 185)
Dan Ibnu Abbas, berkata:
“Tidak mengapa dipisah-pisah (tidak berturut-turut)” (HR. Bukhari)
Abu Hurairah, berkata:
“Diselang-selingi kalau mau” (Lihat Irwaul Ghalil)
Peringatan
Kesimpulannya, tidak ada satupun hadits yang marfu’ dan shahih
-menurut pengetahuan kami- yang mejelaskan keharusan memisahkan atau
secara berturut-turut dalam mengqadha’, namun yang lebih mendekati
kebenaran dan mudah (dan tidak memberatkan kaum muslimin) adalah
dibolehkan kedua-duanya. Demikian pendapatnya
Imam Ahlus Sunnah Ahmad bin Hanbal Rahimahullah.
Abu Dawud berkata, dalam Al-Masail-nya hal. 95 :
“Aku mendengar Imam Ahmad ditanya tentang qadha’ Ramadhan” Beliau
menjawab : “Kalau mau boleh dipisah, kalau mau boleh juga
berturut-turut”. Wallahu ‘alam.
Oleh karena itu dibolehkannya memisahkan tidak menafikan dibolehkannya secara berturut-turut.
Begitu pula orang yang tidak mampu puasa, tidak boleh dipuasakan oleh
anaknya selama dia hidup, tapi dia harus mengeluarkan makanan setiap
harinya untuk seorang miskin, sebagaimana yang dilakukan Anas dalam satu
atsar yang kami bawakan tadi. Namun barangsiapa yang wafat dalam
keadaan mempunyai hutang nadzar puasa, harus dipuasakan oleh walinya.
Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam, bersabda :
“Barangsiapa yang wafat dan mempunyai hutang puasa nadzar hendaknya diganti oleh walinya” (HR. Bukhari MUslim)
Dan dari Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘Anhuma, ia berkata:
“Datang seseorang kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam
kemudian berkata : “Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku wafat dan dia
punya hutang puasa setahun, apakah aku harus membayarnya?” Rasulullah
Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab : “Ya, hutang kepada Allah lebih
berhak untuk dibayar” (HR. Bukhari dan Muslim)
Hadits-hadits umum ini menegaskan disyariatkannya seorang wali untuk
puasa (mempuasakan) mayit dengan seluruh macam puasa, demikian pendapat
sebagian
Syafi’iyah dan madzhabnya Ibnu Hazm .
Tetapi hadits-hadits umum ini dikhususkan, seorang wali tidak puasa
untuk mayit kecuali dalam puasa nadzar, demikian pendapat Imam Ahmad
seperti yang terdapat dalam Masa’il Imam Ahmad riwayat Abu Dawud, dia
berkata : Aku mendengar
Ahmad bin Hambal berkata :
“Tidak berpuasa atas mayit kecuali puasa nadzar”. Abu Dawud berkata,
“Puasa Ramadhan ?”. Beliau menjawab, “Memberi makan”.
Inilah yang menenangkan jiwa, melapangkan dan mendinginkan hati,
dikuatkan pula oleh pemahaman dalil karena memakai seluruh hadits yang
ada tanpa menolak satu haditspun dengan pemahaman yang selamat khususnya
hadits yang pertama.
Aisyah tidak memahami hadits-hadits tersebut secara mutlak yang
mencakup puasa Ramadhan dan lainnya, tetapi dia berpendapat untuk
memberi makan (fidyah) sebagai pengganti orang yang tidak puasa
Ramadhan, padahal beliau adalah perawi hadits tersebut, dengan dalil
riwayat ‘Ammarah bahwasanya ibunya wafat dan punya hutang puasa Ramadhan
kemudian dia berkata kepada Aisyah,
“Apakah aku harus mengqadha’ puasanya ?” Aisyah menjawab : “Tidak,
tetapi bersedekahlah untuknya, setiap harinya setengah gantang untuk
setiap muslim.” (Diriwayatkan Oleh Thahawi dan Ibnu Hazm)
Sudah disepakati bahwa rawi hadits lebih tahu makna riwayat hadits yang ia riwayatkan. Yang berpendapat seperti ini pula adalah
Hibrul Ummah Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘Anhu, berkata:
“Jika salah seorang dari kalian sakit di bulan Ramadhan kemudian
wafat sebelum sempat puasa, dibayarkan fidyah dan tidak perlu qadha’,
kalau punya hutang nadzar diqadha’ oleh walinya.” (Diriwayatkan Oleh Abu
Dawud dan Ibnu Hazm)
Sudah maklum bahwa Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘anhuma adalah periwayatan
hadits kedua, lebih khusus lagi beliau adalah perawi hadits yang
menegaskan bahwa wali berpuasa untuk mayit puasa nadzar.
Sa’ad bin Ubadah minta fatwa kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam :
“Ibuku wafat dan beliau punya hutang puasa nadzar?” Beliau bersabda : “Qadha’lah untuknya.” (HR. Bukhari dan Msulim)
Perincian seperti ini sesuai dengan kaidah ushul syari’at sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim dalam
I’lamul Muwaqi’in dan ditambahkan lagi penjelasannya dalam
Tahdzibu Sunan Abi Dawud.
(Wajib) atasmu untuk membacanya karena sangat penting. Barangsiapa
yang wafat dan punya hutang puasa nadzar dibolehkan diqadha’ oleh
beberapa orang sesuai dengan jumlah hutangnya.
Al-Hasan, berkata :
“Kalau yang mempuasakannya tiga puluh orang seorangnya berpuasa satu hari diperbolehkan.” (Diriwayatkan Oleh Bukhari)
Diperbolehkan juga memberi makan kalau walinya mengumpulkan orang
miskin sesuai dengan hutangnya, kemudian mengenyangkan mereka, demikian
perbuatan Anas bin Malik Radhiyallahu ‘anhu.
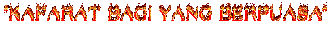
Telah lewat hadits Abu Hurairah, tentang laki-laki yang menjima’i
isterinya di siang hari bulan Ramadhan, bahwa dia harus mengqadha’
puasanya dan membayar kafarat yaitu: membebaskan seorang budak, kalau
tidak mampu makan puasa dua bulan berturut-turut, kalau tidak mampu maka
memberi makan enam puluh orang miskin. Ada yang mengatakan: Kafarat
jima’ itu boleh dipilih secara tidak tertib (yaitu tidak urut seperti
yang dijelaskan dalam hadits Abu Hurairah), tetapi yang meriwayatkan
dengan tertib (sesuai urutannya) perawinya lebih banyak, maka riwayatnya
lebih rajih karena perawinya lebih banyak jumlahnya dan padanya
terdapat tambahan ilmu, mereka sepakat menyatakan tentang batalnya puasa
karena jima’. Tidak pernah terjadi hal seperti ini dalam
riwayat-riwayat lain, dan orang yang berilmu menjadi hujjah atas yang
tidak berilmu, yang menganggap lebih rajih yang tertib disebabkan karena
tertib itu lebih hati-hati, karena itu berpegang dengan tertib sudah
cukup, baik bagi yang menyatakan boleh memilih atau tidak, berbeda
dengan sebaliknya.
Barang siapa yang telah wajib membayar kafarat, namun tidak mampu
mebebaskan seorang budak ataupun puasa (dua bulan berturut-turut) dan
juga tidak mampu memberi makan (enam puluh orang miskin), maka gugurlah
kewajibannya membayar kafarat, karena tidak ada beban syari’at kecuali
kalau ada kemampuan.
Allah Ta’ala, berfirman :
“Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai kemampuan” (Al-Baqarah : 286)
Dan dengan dalil Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam
menggugurkan kafarat dari orang tersebut, ketika mengabarkan
kesulitannya dan memberinya satu wadah korma untuk memberikan
keluarganya.
Seorang wanita tidak terkena kewajiban membayar kafarat, karena
ketika dikhabarkan kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam
perbuatan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan, beliau hanya
mewajibkan satu kafarat saja. Wallahu ‘alam
- Bagi Siapa Fidyah Itu ….. ?
Bagi ibu hamil dan menyusui jika dikhawatirkan keadaan keduanya, maka
diperbolehkan berbuka dan memberi makan setiap harinya seorang miskin.
Allah Ta’ala, Berfirman :
“Dan orang-orang yang tidak mampu berpuasa hendaknya membayar fidyah, dengan memberi makan seorang miskin” (Al-Baqarah : 184)
Sisi pendalilannya, bahwasanya ayat ini adalah khusus bagi
orang-orang yang sudah tua renta (baik laki-laki maupun perempuan),
orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, ibu hamil dan
menyusui, jika dikhawatirkan keadaan keduanya.
Engkau telah mengetahui wahai saudaraku seiman, bahwasanya dalam
pembahasan yang lalu ayat ini mansukh berdasarkan dua hadits Abdullah
bin Umar dan Salamah bin Al-Akwa Radhiyallahuma, tetapi ada riwayat dari
Ibnu Abbas yang menegaskan bahwa ayat ini tidak mansukh dan ini berlaku
bagi laki-laki dan wanita yang sudah tua dan bagi orang yang tidak
mampu berpuasa, maka hendaknya mereka memberi makan setiap hari seorang
miskin” (HR. Bukhari)
Oleh karena itu Ibnu Abbas Radhiyallahu anhuma dianggap menyelisihi
jumhur sahabat atau pendapatnya saling bertentangan, lebih khusus lagi
jika engkau mengetahui bahwasanya beliau menegaskan adanya mansukh.
Dalam riwayat lain (disebutkan),
“Diberi rukhsah bagi laki-laki dan perempuan yang sudah tua yang
tidak mampu berpuasa, hendaknya berbuka kalau mau, atau memberi makan
seorang miskin dan tidak ada qadha’, kemudian dimansukh oleh ayat.
“Karena itu, barangsiapa diantara kamu hadir di bulan itu (Ramadhan)
maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu” (Al-Baqarah : 185)
Telah shahih bagi kakek dan nenek yang sudah tua jika tidak mampu
berpuasa, ibu hamil dan menyusui yang khawatir keadaan keduanya untuk
berbuka, kemudian memberi makan setiap harinya seorang miskin.
(Diriwayatkan Oleh Ibnu Jarud, Al-Baihaqi, dan Abu Dawud)
Sebagian orang ada yang melihat dhahir riwayat yang lalu, yaitu
riwayat Bukhari pada kitab Tafsir dalam Shahihnya yang menegaskan tidak
adanya naskh, hingga mereka menyangka Hibrul Ummat (Ibnu Abbas
Radhiyallahu ‘anhuma) menyelisihi jumhur, tetapi tatkala diberikan
riwayat yang menegaskan adanya naskh, mereka menyangka adanya saling
pertentangan !
Yang benar dan tidak diragukan lagi ayat tersebut adalah mansukh,
tetapi dalam pengertian orang-orang terdahulu, karena Salafus Shalih
Radhiyallahu a’alaihim menggunakan kata nask untuk menghilangkan
pemakaian dalil-dalil umum, mutlak dan dhahir dan selainnya.
Adapun dengan mengkhususkan atau mengaitkan atau menunjukkan yang
mutlak kepada muqayyad, penafsirannya, penjelasannya sehingga mereka
menamakan istisna’ (pengecualian), syarat dan sifat sebagai naskh.
Karena padanya mengandung penghilangan makna dan dhahir maksud lafadz
tersebut.
Naskh dalam bahasa arab menjelaskan maksud tanpa memakai lafadz tersebut, bahkan (bisa juga) dengan sebab dari luar.
Sudah diketahui bahwa barangsiapa yang memperhatikan perkataan mereka
(orang arab) akan melihat banyak sekali contoh masalah tersebut,
sehingga akan hilanglah musykilat (problema) yang disebabkan memaknakan
perkataan Salafus Shalih dengan perngetian yang baru yang mengandung
penghilangan hukum syar’i terdahulu dengan dalil syar’i muataakhirin
yang dinisbatkan kepada mukallaf.
Yang menguatkan hal ini, ayat di atas adalah bersifat umum bagi
seluruh mukallaf yang mencakup orang yang bisa berpuasa atau tidak bisa
puasa. Penguat hal ini dari sunnah adalah apa yang diriwayatkan Imam
Muslim dan Salamah bin Al-Akwa Radhiyallahu ‘anhu:
“Kami pernah pada bulan Ramadhan bersama Rasulullah Shallallahu
‘alaihi wa sallam , barangsiapa yang mau puasa maka puasalah, dan
barangsiapa yang mau berbuka maka berbukalah, tetapi harus berbuka
dengan memberi fidyah kepada seorang miskin, hingga turun ayat :
“Artinya : Karena itu, barangsiapa diantara kamu hadir di bulan itu
(Ramadhan-ed) maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu” (Al-Baqarah :
185)
Mungkin adanya masalah itu terjadi karena hadits Ibnu Abbas yang
menegaskan adanya nash bahwa rukhsah itu untuk laki-laki dan wanita yang
sudah lanjut usia dan tidak mampu berpuasa, tetapi masalah ini akan
hilang jika jelas bagimu bahwa hadits tersebut hanya sebagai dalil bukan
membatasi orangnya, dalil untuk memahami hal ini terdapat pada hadits
itu sendiri. Jika rukhsah tersebut hanya untuk laki-laki dan wanita yang
sudah lanjut usia saja kemudian dihapus (dinaskh), hingga tetap berlaku
bagi laki-laki dan wanita yang sudah lanjut usia, maka apa makna
rukhsah yang ditetapkan dan yang dinafikan itu jika penyebutan mereka
bukan sebagai dalil ataupun pembatasan …? Jika engkau telah merasa jelas
dan yakin, serta berpendapat bahwa makna ayat mansukh bagi orang yang
mampu berpuasa, dan tidak mansukh bagi yang tidak mampu berpuasa, hukum
yang pertama mansukh dengan dalil Al-Qur’an adapun hukum kedua dengan
dalil dari sunnah dan tidak akan dihapus sampai hari kiamat.
Yang menguatkan hal ini adalah pernyataan Ibnu Abbas dalam riwayat yang menjelaskan adanya naskh:
“Telah tetap bagi laki-laki dan wanita yang sudah lanjut usia dan
tidak mampu berpuasa, serta wanita yang hamil dan menyusui jika khawatir
keadaan keduanya, untuk berbuka dan memberi makan orang miskin setiap
harinya”.
Dan yang menambah yang lebih memperjelas lagi adalah hadits Muadz bin Jabal Radhiyallahu ‘Anhu:
“Adapun keadaan-keadaan puasa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa
sallam datang ke Madinah menetapkan puasa selama tiga hari setiap
bulannya, dan puasa Asyura.
Kemudian Allah mewajibkan puasa, maka turunlah ayat :
“Hai orang-orang yang beriman diwajbkan atas kalian berpuasa …”
Kemudian Allah menurunkan ayat :
“Bulan Ramadhan adalah bulan diturunkan padanya Al-Qur’an …”
Allah menetapkan puasa bagi orang mukim yang sehat, dan memberi
rukhsah bagi orang yang sakit dan musafir dan menetapkan fidyah bagi
orang tua yang tidak mampu berpuasa, inilah keadaan keduanya …” (HR.
Abu Dawud, Baihaqi dan Ahmad)
Dua hadits ini menjelaskan bahwa ayat ini mansukh bagi orang yang
mampu berpuasa, dan tidak mansukh bagi orang yang tidak mampu berpuasa,
yakni ayat ini dikhususkan. Oleh karena itu Ibnu Abbas Radhiyallahu
‘anhuma mencocoki sahabat, haditsnya mencocoki dua hadits yang lainnya
(yaitu) hadits Ibnu Umar dan Salamah bin Al-Akwa Radhiyallahu ‘anhum,
dan juga tidak saling bertentangan. Perkataannya tidak mansukh
ditafsirkan oleh perkataannya:
itu mansukh, yakni ayat ini dikhususkan, dengan keterangan ini
jelaslah bahwa naskh dalam pemahaman sahabat berlawanan dengan
pengkhususan dan pembatasan di kalangan ahlus ushul mutaakhirin,
demikianlah diisyaratkan oleh Al-Qurthubi dalam tafsirnya. (Al-Jami’ Li
Ahkamil Qur’an)
Mungkin engkau menyangka wahai saudara muslim hadits dari Ibnu Abbas
dan Muadz hanya semata ijtihad dan pengkhabaran hingga faedah bisa naik
ke tingkatan hadts marfu’ yang bisa mengkhususkan pengumuman dalam
Al-Qur’an dan membatasi yang mutlaknya, menafsirkan yang global, dan
jawabannya sebagai berikut.
- Dua hadits ini memiliki hukum marfu’ menurut
kesepakatan ahlul ilmi tentang hadits Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa
sallam . Seorang yang beriman mencintai Allah dan Rasul-Nya tidak boleh
menyelisihi dua hadits ini jika ia anggap shahih, karena dua hadits ini
ada dalam tafsir ketika menjelaskan asbabun nuzul, yakni dua shahabat
ini menyaksikan wahyu dan turunnya Al-Qur’an, mengabarkan ayat
Al-Qur’an, bahwa turunnya begini, maka ini adalah hadits musnad.
(Tadribur Rawi/Suyuti, dan Ulumul Hadits/Ibnu Shalah)
- Ibnu Abbas menetapkan hukum ini bagi wanita yang
menyusui dan hamil, dari mana beliau mengambil hukum ini …? Tidak
diragukan lagi beliau mengambil dari sunnah, terlebih lagi beliau tidak
sendirian tapi disepakati oleh Abdullah bin Umar yang meriwayatkan bahwa
hadits ini mansukh.
Dari Malik dari Nafi’ bahwasanya Ibnu
Umar ditanya tentang seorang wanita yang hamil jika mengkhawatirkan
anaknya, beliau berkata : “Berbuka dan gantinya memberi makan satu mud
gandum setiap harinya kepada seorang miskin” (Diriwayatkan Oleh Baihaqi
dalam As-Sunnah, dan Imam Syafi’i)
Daruquthni meriwayatkan dari Ibnu Umar dan beliau menshahihkannya, bahwa beliau (Ibnu Umar) berkata :
“Seorang wanita hamil dan menyusui boleh berbuka dan tidak mengqadha”.
Dari jalan lain beliau meriwayatkan :
“Seorang wanita yang hamil bertanya kepada Ibnu
Umar, beliau menjawab : “Berbukalah, dan berilah makan orang miskin
setiap harinya dan tidak perlu mengqadha” (sanadnya jayyid)
Dari jalan yang ketiga Di Sebutkan :
“Anak perempuan Ibnu Umar adalah istri seorang
Quraisy, dan hamil. Dan dia kehausan ketika puasa Ramadhan, Ibnu Umar
pun menyuruhnya berbuka dan memberi makan seorang miskin”
Tidak ada Shahabat yang menentang Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘anhuma. (Di Shahihkan Oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Muhgni)
Keterangan ini menjelaskan makna: “Allah menggugurkan kewajiban puasa
dari wanita hamil dan menyusui” yang terdapat dalam hadits Anas yang
lalu, yakni dibatasi “Kalau mengkhwatirkan diri dan anaknya” dia bayar
fidyah tidak mengqadha.
Barangsiapa menyangka gugurnya puasa wanita hamil dan menyusui sama
dengan musafir sehingga mengharuskan qadha’, perkataan ini tertolak
karena Al-Qur’an menjelaskan makna gugurnya puasa dari musafir.
“Barangsiapa diantara kalian ada yang sakit atau dalam perjalanan
(lalu ia berbuka), maka (wajiblah bagimu berpuasa) sebanyak hari yang
ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain” (Al-Baqarah: 184)
Dan Allah menjelaskan makna gugurnya puasa bagi yang tidak mampu menjalankannya dalam firman-Nya
“Dan wajib bagi orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak
berpuasa) membayar fidyah (yaitu) memberi makan seorang miskin”
(Al-Baqarah : 184)
Maka jelaslah bagi kalian, bahwa wanita hamil dan menyusui termasuk
orang yang tercakup dalam ayat ini, bahkan ayat ini adalah khusus untuk
mereka.
Bagi kaum Muslimin yang melaksanakan Ibadah Puasa maka disyariatkan untuk melaksanakan Shalat Tarawih :
Shalat tarawih disyari’atkan secara berjama’ah.
Dalilnya adalkah hadits Aisyah Radhiyallahu ‘anha :
“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam pada suatu malam keluar dan
shalat di masjid, orang-orang pun ikut shalat bersamanya, dan mereka
memperbincangkan shalat tersebut, hingga berkumpullah banyak orang.
Ketika beliau shalat, mereka-pun ikut shalat bersamanya, mereka
meperbincangkan lagi, hingga bertambah banyaklah penghuni masjid pada
malam ketiga, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam keluar dan
shalat. Ketika malam keempat masjid tidak mampu menampung jama’ah,
hingga beliau hanya keluar untuk melakukan shalat Shubuh. Setelah
selesai shalat beliau menghadap manusia dan bersyahadat kemudian
bersabda. “Artinya : Amma ba’du. Sesungguhnya aku mengetahui perbuatan
kalian semalam, namun aku khawatir diwajibkan atas kalian, sehingga
kalian tidak mampu mengamalkannya” …… Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa
sallam wafat dalam keadaan tidak pernah lagi melakukan shalat tarawih
secara berjama’ah”
(HR. Bukhari dan Muslim)
Ketika Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menemui Rabbnya
(dalam keadaan seperti keterangan hadits diatas) maka berarti syari’at
ini telah tetap, maka shalat tarawih berjama’ah disyari’atkan karena
kekhawatiran tersebut sudah hilang dan ‘illat telah hilang (juga).
Sesungguhnya ‘illat itu berputar bersama ma’lulnya, adanya atau tidak
adanya.
Dan yang menghidupkan kembali sunnah ini adalah Khulafa’ur Rasyidin
Umar bin Al-Khaththab Radhiyallahu ‘Anhu sebagaimana dikabarkan yang demikian oleh Abdurrahman bin Abdin Al-Qoriy beliau berkata :
“Aku keluar bersama Umar bin
Al-Khaththab Radhiyallahu ‘anhu suatu malam di bulan Ramadhan ke masjid,
ketika itu manusia berkelompok-kelompok. Ada yang shalat sendirian dan
ada yang berjama’ah, maka Umar berkata : “Aku berpendapat kalau mereka
dikumpulkan dalam satu imam, niscaya akan lebih baik”. Kemudian beliau
mengumpulkan mereka dalam satu jama’ah dengan imam Ubay bin Ka’ab,
setelah itu aku keluar bersamanya pada satu malam, manusia tengah shalat
bersama imam mereka, Umar-pun berkata, “Sebaik-baik bid’ah adalah ini,
orang yang tidur lebih baik dari yang bangun, ketika itu manusia shalat
di awal malam” (HR. Bukhari)
Manusia berbeda pendapat tentang batasan raka’atnya, pendapat yang
mencocoki petunjuk Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah delapan
raka’at tanpa witir :
Dalilnya adalah hadits Aisyah Radhiyallahu ‘Anha :
“Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak pernah shalat malam di
bulan Ramadhan atau selainnya lebih dari sebelas raka’at” (HR. Bukhari,
Muslim)
Yang telah mencocoki Aisyah adalah Ibnu Umar Radhiyallahu anhuma, beliau menyebutkan :
“Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menghidupkan malam Ramadhan
bersama manusia delapan raka’at kemudian witir.” (HR. Ibnu Hibban,
Thabrani)
Ketika Umar bin Al-Khaththab menghidupkan sunnah ini beliau
mengumpulkan manusia dengan sebelas raka’at sesuai dengan sunnah
shahihah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh
Malik dengan sanad yang shahih dari jalan Muhammad bin Yusuf dari Saib bin Yazid, ia berkata:
“Umar bin Al-Khaththab menyuruh Ubay bin Ka’ab dan Tamim Ad-Daari
untuk mengimami manusia dengan sebelas raka’at”. Ia berkata: “Ketika itu
imam membaca dua ratus ayat hingga kami bersandar/bertelekan pada
tongkat karena lamanya berdiri, kami tidak pulang kecuali ketika furu’
fajar.”
Riwayat beliau ini diselisihi oleh Yazid bin Khashifah, beliau berkata : “Dua puluh raka’at”
Riwayat Yazid ini syadz (ganjil/menyelisihi yang lebih shahih),
karena Muhammad bin Yusuf lebih tsiqah dari Yazid bin Khashifah. Riwayat
Yazid tidak bisa dikatakan ziyadah tsiqah kalau kasusnya seperti ini,
karena ziyadah tsiqah itu tidak ada perselisihan, tapi hanya sekedar
tambahan ilmu saja dari riwayat tsiqah yang pertama sebagaimana (yang
disebutkan) dalam Fathul Mughit, Muhashinul Istilah, Al-Kifayah.
Kalaulah sendainya riwayat Yazid tersebut shahih, itu adalah
perbuatan, sedangkan riwayat Muhammad bin Yusuf adalah perkataan, dan
perkataan lebih diutamakan dari perbuatan sebagaimana telah ditetapkan
dalam ilmu ushul fiqh.
Abdur Razaq meriwayatkan dalam Al-Mushannaf dari Daud bin Qais dan lainnya dari Muhammad bin Yusuf dari Saib bin Yazid:
“Bahwa Umar mengumpulkan manusia di bulan Ramadhan, dengan dua puluh
satu raka’at, membaca dua ratus ayat, selesai ketika awal fajar”
Riwayat ini menyelisihi yang diriwayatkan oleh Malik dari Muhamad bin
Yusuf dari Saib bin Yazid, dhahir sanad Abdur Razaq shahih seluruh
rawinya tsiqah. Sebagian orang-orang yang berhujjah dengan riwayat ini,
mereka menyangka riwayat Muhammad bin Yusuf mudhtharib, hingga
selamatlah pendapat mereka dua puluh raka’at yang terdapat dalam hadits
Yazid bin Khashifah. Sedangkan mereka ini tertolak, karena hadits
mudhtarib adalah hadits yang diriwayatkan dari seorang rawi satu kali
atau lebih, atau diriwayatkan oleh dua orang atau lebih dengan lafadz
yang berbeda-beda, mirip dan sama, tapi tidak ada yang bisa menguatkan
(mana yang lebih kuat). (Lihat Tadribur Rawi)
Namun syarat seperti ini tidak terdapat dalam hadits Muhammad bin
Yusuf karena riwayat Malik lebih kuat dari riwayat Abdur Razaq dari segi
hapalan. Kami ketengahkan hal ini kalau kita anggap sanad Abdur Razaq
selamat dari illat (cacat), akan tetapi kenyatannya tidak demikian
(karena hadits tersebut mempunyai cacat, pent) kita jelaskan sebagai
berikut:
- Yang meriwayatkan Mushannaf dari Abdur Razaq lebih dari seorang, diantaranya adalah Ishaq bin Ibrahim bin Ubbad Ad-Dabari.
- Hadits ini dari riwayat Ad-Dabari dari Abdur Razaq, dia pula yang meriwayatkan Kitabus Shaum. (Al-Mushanaf)
- Ad-Dabari mendengar dari Abdur Razaq karangan-karangannya ketika berumur tujuh tahun. (Mizanul I’tidal)
- Ad-Dabari bukan perawi hadits yang dianggap shahih haditsnya, juga bukan seorang yang membidangi ilmu ini. (Mizanul I’tidal)
- Oleh karena itu dia banyak keliru dalam
meriwayatkan dari Abdur Razaq, dia banyak meriwayatkan dari Abdur Razaq
hadits-hadits yang mungkar, sebagian ahlul ilmi telah mengumpulkan
kesalahan-kesalahan Ad-Dabari dan tashif-tashifnya dalam Mushannaf Abdur
Razaq, dalam Mushannaf. (Mizanul I’tidal)
Dari keterangan di atas maka jelaslah bahwa riwayat
ini mungkar, Ad-Dabari dalam meriwayatkan hadits diselisihi oleh orang
yang lebih tsiqah darinya, yang menentramkan hadits ini kalau kita
nyatakan kalau hadits inipun termasuk tashifnya Ad-Dabari, dia
mentashifkan dari sebelas raka’at (menggantinya menjadi dua puluh satu
rakaat), dan engkau telah mengetahui bahwa dia banyak berbuat tashif.
(Tahdzibut Tahdzib)
Oleh karena itu riwayat ini mungkar dan mushahaf (hasil tashif),
sehingga tidak bisa dijadikan hujjah, dan menjadi tetaplah sunnah yang
shahih yang diriwayatkan di dalam Al-Muwatha’ dengan sanad Shahih dari
Muhammad bin Yusuf dari Saib bin Yazid. Perhatikanlah.
(lihatlah Al-Kasyfus Sharih ‘an Aghlathis Shabun fii Shalatit Tarawih
oleh Syaikh Ali Hasan Abdul Hamid. Al-Mashabih fii Shalatit Tarawih oleh
Imam Suyuthi, dengan ta’liq Syaikh Ali Hasan Abdul Hamid)
Al-Alamah Ibnul Qayyim berkata :
“Manakala hadir dalam keadaan sehat dan istiqamah (konsisten) di atas
rute perjalanan menuju Allah Ta’ala tergantung pada kumpulnya (unsur
pendukung) hati tersebut kepada Allah, dan menyalurkannya dengan
menghadapkan hati tersebut kepada Allah Ta’ala secara menyeluruh, karena
kusutnya hati tidak akan dapat sembuh kecuali dengan menghadapkan(nya)
kepada Allah Ta’ala.
Sedangkan makan dan minum yang
berlebih-lebihan dan berlebih-lebihan dalam bergaul, terlalu banyak
bicara dan tidur, termasuk dari unsur-unsur yang menjadikan hati
bertambah berantakan (kusut) dan mencerai beraikan hati di setiap
tempat, dan (hal-hal tersebut) akan memutuskan perjalanan hati menuju
Allah atau akan melemahkan, menghalangi dan menghentikannya.
Rahmat Allah Yang Maha Perkasa lagi Penyayang menghendaki untuk
mensyariatkan bagi mereka puasa yang bisa menyebabkan hilangnya
kelebihan makan dan minum pada hamba-Nya, dan akan membersihkan
kecenderungan syahwat pada hati yang (mana syahwat tersebut) dapat
merintangi perjalanan hati menuju Allah Ta’ala, dan disyariatkannya
(i’tikaf) berdasarkan maslahah (kebaikan yang akan diperoleh) hingga
seorang hamba dapat mengambil manfaat dari amalan tersebut baik di dunia
maupun di akhirat.
Tidak akan merusak dan
memutuskannya (jalan) hamba tersebut dari (memperoleh) kebaikannya di
dunia maupun di akhirat nanti. Dan disyariatkannya
i’tikaf bagi mereka yang mana maksudnya serta ruhnya adalah berdiamnya
hati kepada Allah Ta’ala dan kumpulnya hati kepada Allah, berkhalwat
dengan-Nya dan memutuskan (segala) kesibukan dengan makhluk, hanya
menyibukkan diri kepada Allah semata. Hingga
jadilah mengingat-Nya, kecintaan dan penghadapan kepada-Nya sebagai
ganti kesedihan (duka) hati dan betikan-betikannya, sehingga ia mampu
mencurahkan kepada-Nya, dan jadilah keinginan semuanya kepadanya dan
semua betikan-betikan hati dengan mengingat-Nya, bertafakur dalam
mendapatkan keridhaan dan sesuatu yang mendekatkan dirinya kepada Allah.
Sehingga bermesraan ketika berkhalwat dengan Allah sebagai ganti
kelembutannya terhadap makhluk, yang menyebabkan dia berbuat demikian
adalah karena kelembutannya tersebut kepada Allah pada hari kesedihan di
dalam kubur manakala sudah tidak ada lagi yang berbuat lembut
kepadanya, dan (manakala) tidak ada lagi yang dapat membahagiakan
(dirinya) selain daripada-Nya, maka inilah maksud dari i’tikaf yang
agung itu.” (Kitab Zaadul Ma’ad)
Yaitu berdiam (tinggal) di atas sesuatu, dapat dikatakan bagi
orang-orang yang tinggal di masjid dan menegakkan ibadah di dalamnya
sebagai mu’takif dan ‘Akif. (Lisanul Arab, dan Al-Mishbahul MUnir)
Disunnahkan pada bulan Ramadhan dan bulan yang lainya sepanjang
tahun. Telah shahih bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam beritikaf
pada sepuluh (hari) terakhir bulan Syawwal. (HR. Bukhari dan Muslim)
Umar pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam :
“Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini pernah bernadzar pada zaman
jahiliyah (dahulu), (yaitu) aku akan beritikaf pada malam hari di
Masjidil Haram’. Beliau menjawab :Tunaikanlah nadzarmu”.
Maka ia (Umar Radhiyallahu ‘anhu) pun beritikaf pada
malam harinya. (HR. Bukhari Dan Muslim)
Yang paling utama (yaitu) pada bulan Ramadhan beradasarkan hadits Abu
Hurairah Radhiyallahu ‘anhu (bahwasanya) Rasulullah Shallallahu ‘alaihi
wa sallam sering beritikaf pada setiap Ramadhan selama sepuluh hari dan
manakala tibanya tahun yang dimana beliau diwafatkan padanya, beliau
(pun) beritikaf selama dua puluh hari. (HR. Bukhari)
Dan yang lebih utama yaitu pada akhir bulan Ramadhan karena Nabi
Shallallahu ‘alaihi wa sallam seringkali beritikaf pada sepuluh (hari)
terakhir di bulan Ramadhan hingga Allah Yang Maha Perkasa dan Mulia
mewafatkan beliau. (HR. Bukhari dan Muslim)
- Tidak disyari’atkan kecuali di masjid, berdasarkan firman-Nya Ta’ala.
“Dan janganlah kamu mencampuri mereka itu, sedangkan kamu beritikaf di dalam masjid” (Al-Baqarah : 187)
- Dan masjid-masjid disini bukanlah secara mutlak
(seluruh masjid ,-pent), tapi telah dibatasi oleh hadits shahih yang
mulai (yaitu) sabda beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam : “Tidak ada
I’tikaf kecuali pada tiga masjid (saja).
Dan sunnahnya bagi
orang-orang yang beritikaf (yaitu) hendaknya berpuasa sebagaimana dalam
(riwayat) Aisyah Radhiyallahu ‘anha yang telah disebutkan. (Diriwayatkan
OLeh Abdur Razak dalam Mushanaf)
- Diperbolehkan keluar dari masjid jika ada hajat,
boleh mengeluarkan kepalanya dari masjid untuk dicuci dan disisir
(rambutnya). Aisyah Radhiyallahu ‘anha berkata.
“Dan sesungguhnya Rasulullah
Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah memasukkan kepalanya kepadaku,
padahal beliau sedang itikaf di masjid (dan aku berada di kamarku)
kemudian aku sisir rambutnya (dalam riwayat lain : aku cuci rambutnya)
[dan antara aku dan beliau (ada) sebuah pintu] (dan waktu itu aku sedang
haid) dan adalah Rasulullah tidak masuk ke rumah kecuali untuk
(menunaikan) hajat (manusia) ketika sedang I’tikaf.” (HR. Bukhari dan
Muslim)
- Orang yang sedang Itikaf dan yang yang lainnya
diperbolehkan untuk berwudhu di masjid, berdasarkan ucapan salah seorang
pembantu Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam ,
“Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam berwudhu di dalam masjid dengan wudhu yang ringan” (Diriwayatkan Oleh Ahmad Sanadnya Shahih)
- Dan diperbolehkan bagi orang yang sedang I’tikaf
untuk mendirikan tenda (kemah) kecil pada bagian di belakang masjid
sebagai tempat dia beri’tikaf, karena Aisyah Radhiyallahu ‘anha (pernah)
membuat kemah (yang terbuat dari bulu atau wool yang tersusun dengan
dua atau tiga tiang) apabila beliau beri’tikaf (Shahih Bukhari) dan hal ini atas perintah Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam . (Shahih Muslim)
- Dan diperbolehkan bagi orang yang sedang beritikaf
untuk meletakkan kasur atau ranjangnya di dalam tenda tersebut,
sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Umar Radhiyallahu ‘anhuma bahwa Nabi
Shallallahu ‘alaihi wa sallam jika i’tikaf dihamparkan untuk kasur atau
diletakkan untuknya ranjang di belakang tiang At-Taubah. (Dikeluarkan
Oleh Ibnu Majah, dan Al-Baihaqi)
- Diperbolehkan bagi seorang isteri untuk
mengunjungi suaminya yang berada di tempat i’tikaf, dan suami
diperbolehkan mengantar isteri sampai ke pintu masjid. Shafiyyah
Radhiyallahu ‘anha berkata.
“Dahulu Nabi Shallallahu ‘alaihi
wa sallam (tatkala beliau sedang) i’tikaf [pada sepuluh (hari) terkahir
di bulan Ramadhan] aku datang mengunjungi pada malam hari [ketika itu di
sisinya ada beberapa isteri beliau sedang bergembira ria] maka aku pun
berbincang sejenak, kemudian aku bangun untuk kembali, [maka beliaupun
berkata: jangan engkau tergesa-gesa sampai aku bisa mengantarmu].
Kemudian beliaupun berdiri bersamaku untuk mengantar aku pulang,
-tempat tinggal Shafiyyah yaitu rumah Usamah bin Zaid- [sesampainya di
samping pintu masjid yang terletak di samping pintu Ummu Salamah]
lewatlah dua orang laki-laki dari kalangan Anshar dan ketika keduanya
melihat Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam , maka keduanyapun bergegas,
kemudian Nabi-pun bersabda : “Tenanglah, ini adalah Shafiyah binti
Huyaiy.” Kemudian keduanya berkata : ‘Subhanahallah (Maha Suci Allah) ya
Rasullullah”. Beliaupun bersabda : “Sesungguhnya syaitan itu menjalar
(menggoda) anak Adam pada aliran darahnya dan sesungguhnya aku khawatir
akan bersarangnya kejelakan di hati kalian -atau kalian berkata
sesuatu.” (Dikeluarkan Oleh BUkhari Dan MUslim)
- Seorang wanita boleh i’tikaf dengan didampingi suaminya ataupun sendirian. berdasarkan ucapan Aisyah Radhiyallahu ‘anha:
“Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam
i’tikaf pada sepuluh hari terakhir pada bulan Ramadhan sampai Allah
mewafatkan beliau, kemudian isteri-isteri beliau i’tikaf setelah itu”
Berkata Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani Rahimahullah :
“Pada atsar tersebut ada suatu dalil yang menunjukkan atas bolehnya
wanita i’tikaf dan tidak diragukan lagi bahwa hal itu dibatasi (dengan
catatan) adanya izin dari wali-wali mereka dan aman dari fitnah,
berdasarkan dalil-dalil yang banyak mengenai larangan berkhalwat dan
kaidah fiqhiyah, Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil
manfaat”
Keutamaannya sangat besar, karena malam
ini menyaksikan turunnya Al-Qur’an Al-Karim, yang membimbing
orang-orang yang berpegang dengannya ke jalan kemuliaan dan
mengangkatnya ke derajat yang mulia dan abadi. Umat Islam yang
mengikuti sunnah Rasulnya tidak memasang tanda-tanda tertentu dan tidak
pula menancapkan anak-anak panah untuk memperingati malam ini, akan
tetapi mereka berloma-lomba untuk bangun di malam harinya dengan penuh
iman dan mengharap pahala dari Allah. Inilah wahai saudaraku muslim,
ayat-ayat Qur’aniyah dan hadits-hadits nabawiyah yang shahih menjelaskan
tentang malam tersebut.
Cukuplah untuk mengetahui tingginya kedudukan Lailatul Qadar dengan
mengetahui bahwasanya malam itu lebih baik dari seribu bulan, Allah
berfirman.
“Sesungguhnya Kami menurunkan Al-Qur’an pada malam Lailatul Qadar,
tahukah engkau apakah malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar itu
lebih baik dari seribu bulan, pada malam itu turunlah melaikat-malaikat
dan Jibril dengan izin Allah Tuhan mereka (untuk membawa) segala
usrusan, selamatlah malam itu hingga terbit fajar.” (Al-Qadar : 1-5)
Dan pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah.
“Sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan
sesungguhnya Kami-lah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan
segala urusan yang penuh hikmah, (yaitu) urusan yang besar dari sisi
Kami. Sesungguhnya Kami adalah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”
(Ad-Dukhan : 3-6)
Diriwayatkan dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bahwa malam
tersebut terjadi pada tanggal malam 21, 23, 25, 27, 29 dan sepuluh akhir
malam bulan Ramadhan.
Imam Syafi’i berkata :
“Menurut pemahamanku. wallahu ‘alam, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa
sallam menjawab sesuai yang ditanyakan, ketika ditanyakan kepada beliau :
“Apakah kami mencarinya di malam ini?”, beliau menjawab : “Carilah di
malam tersebut”. (Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah)
Pendapat yang paling kuat, terjadinya malam Lailatul Qadar itu pada
malam terakhir bulan Ramadhan berdasarkan hadits Aisyah Radhiyallahu
‘anha, dia berkata Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam beri’tikaf
di sepuluh hari terkahir bulan Ramadhan dan beliau bersabda,
“Carilah malam Lailatul Qadar di (malam ganjil) pada 10 hari terakhir bulan Ramadhan”
(HR. Bukhari Muslim)
Jika seseorang merasa lemah atau tidak mampu, janganlah sampai
terluput dari tujuh hari terakhir, karena riwayat dari Ibnu Umar, (dia
berkata) :
Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam, bersabda :
“Carilah di sepuluh hari terakhir, jika tidak mampu maka jangan sampai terluput tujuh hari sisanya”
(HR. Bukhari)
Ini menafsirkan sabdanya
“Aku melihat mimpi kalian telah terjadi, barangsiapa yang mencarinya carilah pada tujuh hari terakhir”
Telah diketahui dalam sunnah, pemberitahuan ini ada karena perdebatan
para sahabat. Dari Ubadah bin Shamit Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata :
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam ke luar pada malam Lailatul
Qadar, ada dua orang sahabat berdebat.
Nabi Sallallahu ‘Alaihi Wa Sallam, bersabda :
“Aku keluar untuk mengkhabarkan kepada kalian tentang malam Lailatul
Qadar, tapi ada dua orang berdebat hingga tidak bisa lagi diketahui
kapannya; mungkin ini lebih baik bagi kalian, carilah di malam 29. 27.
25 (dan dalam riwayat lain : tujuh, sembilan dan lima)”. (HR. Bukhari)
Telah banyak hadits yang mengisyaratkan bahwa malam Lailatul Qadar
itu pada sepuluh hari terakhir, yang lainnya menegaskan, di malam ganjil
sepuluh hari terakhir. Hadits yang pertama sifatnya umum sedang hadits
kedua adalah khusus, maka riwayat yang khusus lebih diutamakan dari pada
yang umum, dan telah banyak hadits yang lebih menerangkan bahwa malam
Lailatul Qadar itu ada pada tujuh hari terakhir bulan Ramadhan, tetapi
ini dibatasi kalau tidak mampu dan lemah, tidak ada masalah, dengan ini
cocoklah hadits-hadits tersebut tidak saling bertentangan, bahkan
bersatu tidak terpisah.
Kesimpulannya
Jika seorang muslim mencari malam lailatul Qadar carilah pada malam
ganjil sepuluh hari terakhir : 21, 23,25,27 dan 29. Kalau lemah dan
tidak mampu mencari pada sepuluh hari terakhir, maka carilah pada malam
ganjil tujuh hari terakhir yaitu 25, 27 dan 29. Wallahu ‘alam
Sesungguhnya malam yang diberkahi ini, barangsiapa yang diharamkan
untuk mendapatkannya, maka sungguh telah diharamkan seluruh kebaikan
(baginya). Dan tidaklah diharamkan kebaikan itu, melainkan (bagi) orang
yang diharamkan (untuk mendapatkannya). Oleh karena itu dianjurkan bagi
muslimin (agar) bersemangat dalam berbuat ketaatan kepada Allah untuk
menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan
pahala-Nya yang besar, jika (telah) berbuat demikian (maka) akan
diampuni Allah dosa-dosanya yang telah lalu.
Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam, bersabda :
“Barang siapa berdiri (shalat) pada malam Lailatul Qadar dengan penuh
keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya
yang telah lalu.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Disunnahkan untuk memperbanyak do’a pada malam tersebut. Telah
diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah Radhiyallahu ‘anha, (dia) berkata :
“Aku bertanya, “Ya Rasulullah ! Apa pendapatmu jika aku tahu kapan malam
Lailatul Qadar (terjadi), apa yang harus aku ucapkan ?” Beliau
menjawab, “Ucapkanlah :
“Allahumma innaka ‘afuwwun tuhibbul afwa fa’fu’annii”
“Ya Allah Engkau Maha Pengampun dan mencintai orang yang meminta ampunan, maka ampunilah aku”
Saudaraku -semoga Allah memberkahimu dan memberi taufiq kepadamu
untuk mentaati-Nya- engkau telah mengetahui bagaimana keadaan malam
Lailatul Qadar (dan keutamaannya) maka bangunlah (untuk menegakkan
shalat) pada sepuluh malam terakhir, menghidupkannya dengan ibadah dan
menjauhi wanita, perintahkan kepada isterimu dan keluargamu untuk itu,
perbanyaklah perbuatan ketaatan.
Dari Aisyah Radhiyallahu ‘Anha, dia berkata :
“Adalah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam , apabila masuk pada
sepuluh hari (terakhir bulan Ramadhan), beliau mengencanngkan kainnya
menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya”
(HR. Bukhari dan Muslim)
Juga Dari Aisyah, dia berkata :
“Adalah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersungguh-sungguh
(beribadah apabila telah masuk) malam kesepuluh (terakhir) yang tidak
pernah beliau lakukan pada malam-malam lainnya” (HR. Muslim)
Ketahuilah hamba yang taat -mudah-mudahan Allah menguatkanmu degan
ruh dari-Nya dan membantu dengan pertolongan-Nya- sesungguhnya
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menggambarkan paginya malam
Lailatul Qadar agar seorang muslim mengetahuinya.
Dari ‘Ubay Radhiyallahu ‘Anhu, ia berkata : Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam, bersabda :
“Pagi hari malam Lailatul Qadar, matahari terbit tidak menyilaukan, seperti bejana hingga meninggi”
(HR. Muslim)
Dari Abu Hurairah, ia berkata : Kami menyebutkan malam
Lailatul Qadar di sisi Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam Lalu
beliau bersabda :
“Siapa di antara kalian yang ingat ketika terbit bulan seperti syiqi jafnah” (HR. Muslim)
Dan dari Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘Anhuma, ia berkata : Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda
“Artinya : (Malam) Lailatul Qadar adalah malam yang indah, cerah,
tidak panas dan tidak juga dingin, (dan) keesokan harinya cahaya sinar
mataharinya melemah kemerah-merahan”. (Diriwayatkan Oleh Thayalisi, Ibnu
Khuzaimah, Al-Bazzar dan Sanadnya Hasan)
Setelahnya kita melaksanakan Ibadah Puasa dibulan Ramadhan, maka kita diwajibkan untuk mengeluarkan Zakat Fithri.
Zakat Fithri ini (hukumnya) wajib berdasarkan hadits (dari)
Ibnu Umar Radhiyallahu ‘anhuma, Ia berkata :
“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam mewajibkan zakat fithri [pada bulan Ramadhan kepada manusia]” (HR. Bukhari dan Muslim)
Dan berdasarkan hadits Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘Anhuma :
“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam mewajibkan zakat fithri” (HR. Abu Dawud dan An-Nasai)
Sebagian Ahul ilmi menyatakan bahwa zakat fithri telah mansukh.
Oleh Hadits Qais bin Sa’ad bin Ubadah, ia berkata:
“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan kami dengan
shadaqah fithri sebelum diturunkan (kewajiban) zakat dan tatkala
diturunkan (kewajiban) zakat beliau tidak memerintahkan kami dan tidak
pula melarang kami, tetapi kami mengerjakannya (mengeluarkan zakat
fithri)”
Al-Hafidz Rahimahullah Menjawab Sangkaan Tersebut :
“Bahwa pada sanadnya ada seorang rawi yang tidak dikenal, dan
kalaupun dianggap shahih tidak ada dalil yang menunjukkan atas naskh
(dihapusnya) hadits Qais yang menunjukkan wajibnya zakat fithri, mungkin
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam mencukupkan dengan perintah
yang pertama, karena turunnya suatu kewajiban tidaklah menggugurkan
kewajiban yang lain”
Imam Al-Kahthabiy Rahimahullah berkata :
“Ini tidak menunjukkan hilangnya kewajiban zakat fithri, tetapi hanya
menunjukkan tambahan dalam jenis ibadah, tidak mengharuskan
dimansukhnya hukum sebelumnya, kedudukan zakat harta (sebagaimana)
kedudukan zakat fithri (yaitu) berkaitan dengan riqab (orang-perorang).”
Zakat fithri atas kaum muslimin, anak kecil, besar, laki-laki, perempuan, orang yang merdeka maupun hamba.
Dalilnya Adalah Hadits Abdullah bin Umar Radhiyallahu ‘Anhuma :
“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam mewajibkan zakat fithri
sebanyak satu gantang kurma, atau satu gantang gandum atas hamba dan
orang yang merdeka, kecil dan besar dari kalangan kaum muslimin”
(HR.
Bukhari dan Muslim)
Sebagian ahlul ilmi ada yang mewajibkan zakat fithri pada hamba yang kafir karena hadits
Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu :
“Hamba tidak ada zakatnya kecuali zakat fithri” (HR. Muslim)
Hadits ini umum sedang hadits Ibnu Umar khusus, sudah maklum hadits
khusus jadi penentu hadits umum. Yang lain berkata, “Tidak wajib atas
orang yang puasa karena hadits
Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘Anhuma :
“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam mewajibkan zakat fithri,
pensuci bagi orang yang puasa dari perbuatan sia-sia, yang jelek dan
(memberi) makanan bagi orang miskin”
Imam Al-Khathabiy menegaskan:
“Zakat fithri wajib atas orang yang puasa yang kaya atau orang fakir
yang mendapatkan makanan dari dia, jika illat diwajibkannya karena
pensucian, maka seluruh orang yang puasa butuh akan hal itu, jika
berserikat dalam ‘illat berserikat pula dalam hukum” (Ma’alimul Sunnah)
Al-Hafidz Menjawab :
“Pensucian disebutkan untuk menghukumi yang dominan, zakat fithri
diwajibkan pula atas orang yang tidak berpuasa seperti diketahui
keshahihannya atau orang yang masuk Islam sesaat sebelum terbenamnya
matahari.”
Sebagian lagi berpendapat bahwa zakat fithri wajib juga atas janin,
tetapi kami tidak menemukan dalil akan hal itu, karena janin tidak bisa
disebut sebagai anak kecil atau besar, baik menurut masyarakat maupun
istilah.
Zakat dikeluarkan berupa satu gantang gandum, satu gantang korma, satu gantang susu, satu gantang anggur kering atau salt,
Dalilnya Adalah hadits Abu Sa’id Al-Khudri Radhiyallahu ‘Anhu :
“Kami mengeluarkan zakat (pada zaman Rasulullah Shallallahu ‘alaihi
wa sallam ) satu gantang makanan, satu gantang gandum, satu gantang
korma, satu gantang susu kering, satu gantang anggur kering”
(HR.
Bukhari, Muslim)
Dan hadits Ibnu Umar Radhiyallalhu ‘Anhuma :
“Rasulullah mewajibkan satu gantang gandum, satu gantang korma dan satu gantang salt”
(Dikeluarkan Oleh Ibnu Khuzaimah)
Telah ikhtilaf dalam tafsir lafadz makanan dalam hadits Abu Said
Al-Khudri ada yang bilang hinthah (gandum yang bagus) ada yang bilang
selain itu, namun yang paling kuat (yang membuat hati ini tenang) lafadz
di atas mencakup seluruh yang dimakan termasuk hinthah dan jenis
lainnya, tepung dan adonan, semuanya telah dilakukan oleh para sahabat
berdasarkan hadits
Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘Anhuma :
“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menyuruh kami untuk
mengeluarkan zakat Ramadhan satu gantang makanan dari anak kecil, besar,
budak dan orang yang merdeka. Barangsiapa yang memberi salt (sejenis
gandum yang tidak berkulit) akan diterima, kau mengira beliau berkata,
“Barangsiapa yang mengeluarkan berupa tepung akan diterima, barangsiapa
yang menerima berupa adonan diterima.”
Dan beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda.
“Zakat Fithri satu gantang makanan, barangsiapa yang membawa gandum
diterima, yang membawa korma diterima, yang membawa salt (gandum yang
tidak berkulit) diterima, yang membawa anggur kering diterima, aku
mengira beliau berkata : “Yang membawa adonan diterima.”
(Dikeluarkan
Oleh Ibnu Khuzaimah dengan Sanad yang Hasan)
Adapun hadits-hadits yang menafikan adanya
hinthah (gandum)
atau bahwasanya Muawiyah Radhiyallahu ‘anhua berpendapat untuk
mengeluarkan dua mud dari samara (gandum) Syam, dan bahwa satu mud
hinthah sebanding, ini dimungkinkan karena jarangnya dan banyaknya jenis
lain, atau karena jenis-jenis hinthah itu melebihi yang ada di sini.
Ini dikuatkan oleh perkataan Abu Sa’id : “Dulu makanan kami adalah
gandum, anggur kering, susu yang dikeringkan dan korma.”
Yang membantah seluruh dalil orang yang menyelisihi kita adalah satu
pembahasan yang akan datang ketika menjelaskan takaran zakat fithri,
menurut hadits-hadits shahih yang menegaskan adanya hinthah bahwa dua
mud
hinthah sama dengan satu gantang anggur, agar kaum muslimin
yang mendudukan sahabat sesuai dengan kedudukan mereka, bahwa pendapat
Mu’awiyah bukanlah ijtihad hasil pikiran sendiri, tetapi berdasarkan
hadist marfu’ sampai kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam .
Seorang muslim diperbolehkan zakat fithri sesuai dengan jenis yang
disebutkan tadi, mereka ikhtilaf tentang hinthah, ada yang mengatakan
setengah gantang ini yang rajih, dan yang paling shahih berdasarkan
sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam .
“Tunaikanlah satu gantang gandum atau korma, untuk dua orang satu
gantang dari gandum atas orang merdeka, hamba, anak kecil atau besar”
(Dikeluarkan Oleh Ahmad)
Gantang yang teranggap adalah gantang-nya penduduk Madinah.
Berdasarkan Hadits Ibnu Umar Radhiyallahu ‘Anhuma :
“ Timbangan yang teranggap adalah timbangannya Ahlu Mekah,
dan kiloan yang teranggap adalah kiloan-nya orang Madinah” (Riwayat Abu
Dawud)
Seorang muslim harus mengeluarkan zakat fithri untuk dirinya dan
seluruh orang yang dibawah tanggungannya, baik anak kecil ataupun orang
tua laki-laki dan perempuan, orang yang merdeka dan budak.
Berdasarkan Hadits Ibnu Umar Radhiyallahu ‘Anhuma:
“Kami diperintah oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam
(mengeluarkan) shadaqah fithri atas anak kecil dan orang tua, orang
merdeka dan hamba dari orang-orang yang membekalinya” (Dikeluarkan Oleh
Daruqutni, Baihaki)
Zakat tidak boleh diberikan kecuali kepada orang yang berhak menerimanya, mereka adalah orang-orang miskin.
Berdasarkan Hadits Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘Anhuma :
“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam zakat fithri sebagai
pembersih (diri) bagi yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perbuatan
kotor dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin”
Pendapat inilah yang dipilih oleh Syaikhul Islam di dalam
Majmu’ Fatawa serta murid beliau Ibnul Qayyim pada kitabnya yang bagus
Zaadul Ma’ad .
Sebagian Ahlul ilmi berpedapat bahwa zakat fithri diberikan kepada
delapan golongan, tetapi (pendapat) ini tidak ada dalilnya. Dan Syaikhul
Islam telah membantahnya pada kitab yang telah disebutkan baru saja,
maka lihatlah ia, karena hal tersebut sangat penting. Termasuk amalan
sunnah jika ada seseorang yang bertugas mengumpulkan zakat tersebut
(untuk dibagikan kepada yang berhak, -pent).
Sungguh Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam telah mewakilkan kepada Abu Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu, ia berkata:
“Rasulullah mengkhabarkan kepadaku agar aku menjaga zakat Ramadhan” (Dikeluarkan Oleh Bukhari)
Dan sungguh dahulu pernah Ibnu Umar radhiyallahu ‘anuma mengeluarkan
zakat kepada orang-orang yang menangani zakat dan mereka adalah panitia
yang dibentuk oleh Imam (pemerintah, -pent) untuk mengumpulkannya.
Beliau (Ibnu Umar) mengeluarkan zakatnya satu hari atau dua hari sebelum
Idul fithri, dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah dari jalan Abdul Warits
dari Ayyub, aku katakan :
“Kapankah Ibnu Umar mengeluarkan satu gantang?” Berkata Ayyub :
“Apabila petugas telah duduk (bertugas)”. Aku katakan : ‘Kapankah
petugas itu mulai bertugas?” Beliau menjawab : “Satu hari atau dua hari
sebelum Idul Fithri”.
Zakat fithri ditunaikan sebelum orang-orang keluar (rumah) menuju
shalat ‘Id[3] dan tidak boleh diakhirkan (setelah) shalat atau dimajukan
penunaiannya, kecuali satu atau dua hari (sebelum Id) berdasarkan
riwayat perbuatan Ibnu Umar Radhiyallahu ‘anhuma berdasarkan kaidah rawi
hadits diketahui dengan makna riwayat dan apabila penunaian zakat itu
diakhirkan (setelah) shalat maka dianggap sebagai shadaqah.
Berdasarkan Hadits Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘Anhuma :
“… Barangsiapa yang menunaikan zakatnya sebelum shalat maka dia
adalah zakat yang diterima, dan barangsiapa yang menunaikannya setelah
shalat maka dia adalah merupakan suatu shadaqah dari beberapa shadaqah”
Allah Ta’ala mewajibkan zakat sebagai penscucian diri bagi
orang-orang yang berpuasa dari (perbuatan) sia-sia dan kotor serta
sebagai makanan bagi orang-orang miskin untuk mencukupi (kebutuhan)
mereka pada hari yang bagus tersebut berdasarkan hadits dari Ibnu Abbas
Radhiyallahu ‘anhuma yang telah lalu.